MATERI Antropologi Hukum
BAHAN KULIAH ANTROPOLOGI HUKUM
I. HUKUM dan KEBUDAYAAN
Seperti
dipahami bersama bahwa ilmu-ilmu hukum mencakup normwissenschaften yang menyoroti hukum dari sudut normatif, dan tatsachenwissenschaften yang menelaah
hukum sebagai perikelakuan yang merupakan kenyataan dalam masyarakat. Salah
satu ilmu bantu hukum yang menyoroti hukum dari aspek perilaku adalah
antropologi hukum. Dalam tataran normatif yang dipelajari adalah asas hukum dan
kaedah hukum. Asas hukum merupakan nilai, dan nilai merupakan inti dari
kebudayaan yang menjadi tinjauan utama dari antropologi. Dari sudut
antropologi, kita akan mengetahui latar belakang dari kaedah/norma hukum atau
asas hukum/nilai hukum.
Sebenarnya
pada kuliah AH kita akan langsung masuk ke materi AH, tetapi dengan
pertimbangan peserta kuliah belum tentu pernah mengambil/mengikuti mata kuliah
Antropologi Budaya (AB), karena mata kuliah AB merupakan mata kuliah pilihan.
Dengan pertimbangan itu, maka pada awal kuliah dibuka dulu dengan hal-hal yang
terkait antara kebudayaan dengan hukum, dengan memberikan pengertian
kebudayaan, bentuk-bentuk kebudayaan, dan hubungan antara kebudayaan dengan
hukum.
Kebudayaan
Kebudayaan
menurut Prof.Dr. Koentjaraningrat dalam
bukunya Pengantar Antropologi I (1996:72) adalah seluruh sistem gagasan dan
rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan
bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dengan demikian hampir
semua tindakan manusia adalah “kebudayaan”, karena jumlah tindakan yang
dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakannya dengan
belajar (naluri, refleks, tindakan akibat proses fisiologi, tindakan
membabi-buta), sangat terbatas. Bahkan tindakan yang bersifat naluri (makan,
minum, berjalan) juga telah banyak dirombak oleh manusia sehingga menjadi
tindakan kebudayaan. Manusia makan pada waktu tertentu dengan cara tertentu,
sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Demikian juga cara berjalan, berbeda
antara orang kebanyakan dengan cara berjalan prajurit militer atau peragawati,
inipun sebagai tindakan kebudayaan yang dibiasakan dengan belajar.
Kebudayaan
(culture), perlu dibedakan dengan
peradaban (civilization). Peradaban
adalah istilah yang dipakai untuk menyebut bagian-bagian/unsur-unsur dari
kebudayaan yang sifatnya halus, maju dan
indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan-santun dan pergaulan,
kepandaian menulis, organisasi bernegara dan lain-lain. Istilah peradaban juga
sering dipakai untuk menyebut bagian kebudayaan seperti teknologi, ilmu
pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, masyarakat kota yang maju dan
kompleks.
Wujud Kebudayaan
Wujud
kebudayaan, menurut Prof Koentjaraningrat (1996: 56) digambarkan dalam 4
lingkaran konsentris yaitu :
1.
Lingkaran inti adalah nilai-nilai budaya (sistem ideologis)
2.
Lingkaran kedua dari dalam adalah sistem budaya (sistem gagasan)
3.
Lingkaran ketiga adalah sistem sosial (sistem tingkah laku)
4.
Lingkaran keempat adalah kebudayaan fisik (benda-benda fisik).
Contoh dari wujud konkret kebudayaan
(lingkaran/wujud keempat) antara lain bangunan-bangunan megah, benda-benda
bergerak, dan semua benda hasil karya manusia yang bersifat konkrit dan dapat
diraba serta difoto. Wujud ketiga/sistem tingkah laku, meliputi menari,
berbicara, tingkah laku melakukan pekerjaan, semua gerak-gerik dan dari hari ke
hari, merupakan pola-pola tingkah laku yang dilakukan berdasarkan sistem
sosial.Wujud ketiga ini masih bisa dipotret dan konkret.
Sedangkan wujud kedua/ sistem gagasan,
tempatnya pada kepala tiap individu warga kebudayaan. Wujud kedua ini bersifat
abstrak, tak dapat difoto, dan hanya dipahami (oleh warga kebudayaan lain)
setelah ia mempelajari melalui wawancara atau dengan membaca apa yang dia
tulis. Berikutnya wujud pertama/ sistem ideologis, adalah gagasan-gagasan yang
telah dipelajari oleh para warga sejak usia dini, dan karenanya sukar diubah,
disebut juga “nilai-nilai budaya” yang menentukan sifat dan corak pikiran, cara
berpikir serta tingkah laku manusia suatu kebudayaan.
Hubungan Hukum Dengan Kebudayaan
Dalam AH, hukum ditinjau sebagai aspek dari
kebudayaan. Manusia dalam hidup bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku
dengan menjunjung tingi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya, yang
oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu
dianggap penting oleh warga masyarakat lain. Nilai-nilai budaya tercakup secara
lebih konkret dalam norma-norma sosial, yang diajarkan kepada setiap warga
masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai
peranan dalam berbagai situasi sosial.
Norma-norma sosial sebagian tergabung dalam
kaitan dengan norma lain, dan menjelma sebagai pranata atau lembaga sosial yang
semuanya lebih mempermudah manusia mewujudkan perilaku yang sesuai dengan
tuntutan masyarakatnya atau yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara
hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal atau desain hidup atau
cetak biru, yang merupakan kebudayaan dari masyarakat itu hendak dilestarikan
melalui cara hidup warga masyarakat, dan salah satu cara untuk mendorong para
anggota masyarakat supaya melestarikan kebudayaan itu adalah hukum.
Contoh untuk menjelaskan hubungan hukum dan
kebudayaan akan diberikan contoh mengenai hubungan kekerabatan dalam sistem
kekerabatan di Bali. Menurut kebudayaan Bali, perhitungan garis keturunan
adalah suatu hal yang sangat penting. Nilai utamanya adalah gagasan bahwa anak
laki-laki diakui sebagai pengubung dalam garis keturunan. Hal ini menghasilkan
norma sosial, yaitu seseorang mempertimbangkan garis keturunannya melalui ayah
sehingga dapat dikonstruksikan (secara1 konseptual) suatu garis keturunan yang
berkesinambungan, yang menghubungkan para laki-laki sebagai
penghubung-penghubung garis keturunan. Norma sosial mengenai garis keturunan
itu berhubungan dengan norma sosial lainnya dalam kaitan dengan pengaturan
soal-soal yang berkenaan dengan
kekerabatan, seperti norma sosial bahwa seseorang istri harus mengikuti suami
ke tempat tinggal kerabat dari suaminya (patrilokal), norma sosial yang lain,
harta dari seorang ayah diwariskan pada anaknya yang laki-laki. Norma sosial
ini semuanya bergabung menjadi suau
lembaga atau pranata sosial, yaitu
pranata atau lembaga keluarga. Pranata ini diikuti sebagai pedoman berlaku oleh
semua anggota masyarakat, bila ada anggota masyarakat tidak mengindahkan norma
sosial itu, maka ini berarti nilai budaya yang mendasarinya diingkari, dan jika
pelanggaran itu sering terjadi, maka nilai budaya yang mendasarinya, lama-lama
akan memudar dan terancam hilang.
Sebagian dari norma sosial itu kalau
dilanggar akan memperoleh sanksi yang konkret yang dikenakan oleh petugas hukum
atau wakil-wakil rakyat yang diberi wewenang untuk itu. Sebagai contoh, ada seorang istri di Bali tidak mau mengikuti
suami ke tempat tinggal kerabatnya, maka ia akan dikenakan sanksi yaitu
diceraikan. Jadi sebagian dari nilai-nilai budaya yang tercermin dalam norma
sosial juga dimasukkan ke dalam peraturan hukum, dan karena perlindungannya
terjadi melalui proses hukum, maka usaha mencegah pelanggarannya dengan sanksi
hukum, dibandingkan dengan norma sosial yang merupakan kebiasaan saja.
II. PENGERTIAN ANTROPOLOGI HUKUM
Definisi Antroplogi Hukum
Menurut Prof. Dr. T.O. Ihromi (1984:24) Antropologi Hukum adalah cabang
dari antropologi budaya yang hendak
memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi
melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum.
Sedangkan Prof. Dr. Nyoman Nurjaya (2008:47) melihat definisi AH dari dua
sudut. Dari optik ilmu hukum, AH pada
dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya
pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Jika dilihat
dari sudut antropologi, AH adalah sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan
kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat.
Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari
hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat,
bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum
bekerja sebagai alat pengendalian sosial (social
control) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat. Antroplogi Hukum merupakan salah satu ilmu empiris atau ilmu
perilaku yang menitik beratkan pada
pemahaman hukum dalam sudut
pandang empiris/kenyataan yaitu ilmu antropologi. Pemahaman terhadap
suatu kenyataan dalam bahasa sosiologi disebut verstehen, menjelaskan mengapa suatu perbuatan itu terjadi.
Dikaitkan dengan kajian hukum, maka yang dipahami adalah mengapa orang yang
satu melakukan tindakan yang berbeda dengan orang yang lain pada hal aturan
yang berlaku bagi orang-orang tersebut sama. Latar belakang inilah yang ingin
dicari penjelasannya dari kacamata antropologi hukum. Perspektif ini berbeda
dengan perspektif hukum yang menjustifikasi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau
kejahatan.
Manfaat Mempelajari Antropologi Hukum
Para praktisi hukum seringkali ragu-ragu
mengenai apakah ada manfaat yang dapat diambil dari AH. Mereka berkilah bahwa
telaah AH akan memperdalam pemahaman mengenai proses
pengendalian sosial, latar belakang budaya dari hukum, tetapi hasilnya tidak
dapat langsung digunakan. Hal itu memang benar, karena fungsinya
lebih besar pencegahan atau preventif daripada represif, dengan mengetahui
latar belakang budaya dari suatu masyarakat
dalam pengendalian sosial akan dengan mudah mengendalikan masyarakat
yang kurang atau tidak tahu hukum negara.
Jadi manfaat
mempelajari AH adalah untuk mengetahui gambaran bekerjanya hukum sebagai
pengendali sosial yang dilatar-belakangi oleh budaya.
Ruang Lingkup Antropologi Hukum
Ruang lingkup antropologi hukum dapat
dijelaskan dengan membandingkan dengan ilmu-ilmu yang dekat dengannya, yaitu
dengan hukum adat dan sosiologi hukum. Ada ahli antropologi yang menyamakan
hukum adat dengan antropologi hukum. Pendapat ini tidaklah salah karena pokok
perhatian kedua ilmu ini bukan pada masyarakat yang sudah maju seperti di
Barat, tetapi pada masyarakat sederhana dimana kehidupan hukum dan budayanya
belum kompleks. Selain itu kedua-duanya mempelajari gejala sosial. Bahkan hari
lahirnya hukum adat yaitu 3 Oktober 1901 ketika van Vollenhoven menyampaikan
kuliah inaugurasinya di Universitas Leiden, oleh ahli antropologi hukum John
Griffiths disebut juga lahirnya Antropologi Hukum.
G.J.Resink, guru besar FHUI, seperti dikutip
Prof. T.O. Ihromi, mengatakan dalam banyak hal sebenarnya pendekatan-pendekatan dan
metode-metode yang sekarang digunakan dalam AH, juga telah menjadi tradisi
dalam ilmu hukum adat. Bahkan sudah jauh-jauh hari Ter Haar menggunakan istilah
etnologi hukum, sehingga dapatlah diterima bahwa bidang yang ditelaah oleh
AH dengan hukum adat, untuk bagian besar
banyak persamaannya. Bahan-bahan hukum adat dapat dimanfaatkan dalam
pengembangan AH di Indonesia, demikian
sebaliknya metode-metode penelitian dalam AH juga dapat bermanfaat bagi hukum
adat itu sendiri.
Perbedaannya, dalam hukum adat yang diutamakan adalah identifikasi dari adat
yang mempunyai konsekuensi hukum. Sedangkan Antropologi Hukum, disamping mempelajari norma
hukum juga ditelaah berbagai jenis pedoman perilaku serta hubungan di antara
aneka norma itu dengan nilai-nilai budaya yang dianut dalam suatu masyarakat.
Jadi dapat dikatakan bahwa wawasan AH lebih luas karena tidak hanya memperhatikan hukum di Indonesia,
tetapi juga bersifat komparatif sehingga hukum ditinjau sebagai gejala yang
bersifat lintas budaya.
Perbedaaan antara antropologi hukum dengan
hukum adat dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1
Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat
|
No
|
Item
|
Antroplogi Hukum
|
Hukum Adat
|
|
1
|
Obyek
|
Perilaku manusia
|
Norma hukum di luar UU
|
|
2
|
Pendekatan
|
Holistik
|
Yuridis normatif
|
|
3
|
Sifat Penelitian
|
Penelitian lapangan
|
Studi pustaka & dokumen
|
|
4
|
Norma
|
Kenyataan
|
Dikehendaki
|
Dari tabel diatas terlihat bahwa obyek AH adalah perilaku hukum dari
manusia, sedangkan sasarannya adalah norma-norma hukum yang dipakai oleh
anggota masyarakat. Selanjutnya pendekatan yang dipakai AH adalah holistik,
dari kata whole, artinya dalam mempelajari
sesuatu akan dilihat secara keseluruhan. Meminjam teori sistem, hukum hanyalah
entitas sub sistem yang dipengaruhi dan mempengaruhi oleh sub-sub sistem yang
lain, misalnya sub sistem ekonomi, sub sistem politik, sub sistem sosial dan
lain sebagainya. Kemudian dilihat dari sifat penelitian, pada AH lebih
menitik-beratkan pada penelitian lapangan (field
research) dari pada studi pustaka. Sebaliknya hukum adat, lebih
mengutamakan studi pustaka dan dokumen dari pada penelitian lapangan.
Untuk melihat ruang lingkup AH, juga akan
diperlihatkan perbedaannya dengan Sosiologi Hukum (SH), karena ilmu yang disebut terakhir ini juga
mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan AH. Ada yang mengatakan antara AH
dan SH adalah seperti dua sisi mata uang
logam, bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2
Perbedaan Antropologi Hukum dengan Sosiologi
Hukum
|
No
|
Item
|
Antropologi Hukum
|
Sosiologi Hukum
|
|
1
|
Obyek
|
Hukum bukan Barat, tidak tertulis
|
Hukum Barat/ yang telah dipengaruhi, hk
tertulis
|
|
2
|
Subyek
|
Masyarakat sederhana
|
Masyarakat maju/modern
|
|
3
|
Perspektif
|
Budaya
|
Sosial
|
|
4
|
Penelitian
|
Kualitatif, studi kasus
|
Kuantitatif, Sampel
|
Perbedaan di atas adalah perbedaan pada
awalnya, dalam perkembangannya sudah mengalami perubahan, bahkan sulit untuk
dibedakan, misalnya obyek dan subyek sudah bercampur mulai dari masyarakat
sederhana sampai masyarakat maju/modern.
Hal-hal yang masih bisa dibedakan adalah menyangkut perspektif dan
metode penelitian yang masing-masing mempunyai ciri khas.
Pendekatan Antropologi Hukum
Berbicara mengenai pendekatan, adalah
berbicara bagaimana cara suatu ilmu pengetahuan mendekati obyek/sasaran
kajiannya. Pendekatan AH setidaknya ada tiga yaitu, holistik, empiris, dan
komparatif. Pendekatan holistik artinya, AH melihat gejala sosial yang ada
dengan kacamata menyeluruh, dari berbagai sudut pandang, tidak stereotip, yaitu
hukum dipandang bukan hanya hukum secara an
sich, tetapi dilihat dari sudut pandang dan kaitan fungsinya dengan yang
lain, misalnya ekonomi, politik, sosial, agama dan lain sebagainya.
Sebagai ilmu perilaku/empiris, AH lebih
menitik-beratkan pada kenyataan-kenyataan hukum yang nampak dalam situasi atau
peristiwa hukum (law in actions)
tidak hukum dalam peraturan perundangan tertulis (law in book). Dalam arti
lain, AH sebagai ilmu empiris mempunyai konsekuensi bahwa teorinya harus
didukung oleh fakta yang relevan atau setidaknya terwakili secara
representatif. Mengikuti pendekatan sejarah, maka metode komparatif dapat
dilakukan dengan cara penelitian sinkronis (generalizing
approach) maupun penelitian diakronis (descriptive
approach). Dalam penelitian sinkronis, mencari prinsip persamaan diantara berbagai kebudayaan.
Sedangkan metode komparatif yang diakronis, meneliti suatu masyarakat tertentu
dari waktu ke waktu atau perkembangan suatu masyarakat tertentu.
III. PERKEMBANGAN ANTROPOLOGI HUKUM
Awal pemikiran antroplogis tentang hukum dimulai dengan
studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi, bukan dari kalangan
sarjana hukum. Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya
klasik Sir Henry Maine yang bertajuk The
Ancient Law yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Ia dipandang
sebagai peletak dasar studi antropologis tentang hukum melalui introduksi teori
evolusionistik mengenai masyarakat dan hukum. Secara umum tema
kajian/teori-teori AH dapat dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu Fase
Evolusionisme, Fase Fungsionalisme, Fase Pluralisme.
Fase Evolusionisme (1861-1926)
Tema-tema kajian yang dominan pada fase
evolusionisme/awal perkembangan AH adalah berkisar pada eksistensi hukum.
Perspektif pada fase ini adalah adanya anggapan hukum berevolusi/berkembang
sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.
Studi evolusionistik AH dimulai oleh Sir Henry Maine dalam bukunya The Ancient Law (1861), yang mengatakan
bahwa perkembangan hukum menyesuaikan dengan
perkembangan masyarakatnya, yang
dimulai dari masyarakat purba, masyarakat suku, dan masyarakat wilayah bersama.
Menurut Maine, pada masyarakat purba,
masyarakatnya masih disibukkan dengan urusan makanan dan melangsungkan
keturunan, sehingga dikatakan pada waktu itu belum ada hukum. Kemudian
masyarakat suku menyadari bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama.
Kesadaran ini membentuk ikatan hubungan darah yang disebut masyarakat suku (tribal society). Pada masyarakat suku
ini, kata Maine pada dasarnya masih belum ada hukum, tetapi dikatakan ada hukum
jika hukum tersebut berlaku secara kontinyu bukan secara insidental.
Kemudian masyarakat suku timbul kesadaran
baru bahwa suku-suku yang ada bertempat tinggal pada teritorial bersama,
sehingga terbentuk masyarakat wilayah bersama. Pada masyarakat ini sudah
terbentuk pemerintahan baik monarki maupun republik. Perkembangan hukum pada
masyarakat ini dibedakan menjadi dua, masyarakat wilayah bersama yang statis
(diluar Eropa dan Amerika Utara) hukumnya masih sederhana, sedangkan pada
masyarakat wilayah bersama yang dinamis, bentuk hukumnya sudah kompleks dan
modern.
Tokoh kedua pada fase evolusionisme adalah
J.J. Bachofen dengan bukunya Das
Mutterecht (terbit 1861). Menurut
Bachofen perkembangan masyarakat dimulai dari Gemeinschaft menuju masyarakat gesselschaft.
Masyarakat Gemeinschaft adalah suatu
masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kesersamaan, kekeluargaan,
gotong-royong dalam kehidupannya. Pada masyarakat ini bentuk hukumnya mengikuti
masyarakatnya, artinya hukum yang terbentuk masih mengutamakan hal-hal yang
sifatnya komunal. Kemudian pada masyarakat gesselschaft
adalah suatu masyarakat yang sudah menggunakan rasionalisme, individualisme,
dan ekonomis dalam kehidupannya. Demikian pula hukum yang terbentuk pada
masyarakat ini menempatkan kepentingan pribadi, rasionalitas dan ekonomis di
atas kepentingan bersama.
Fase Fungsionalisme (awal abad ke-20)
Selanjutnya pada fase fungsionalisme ini, terjadi perdebatan apa itu hukum, apakah
hukum ada pada semua masyarakat, dari
para peminat AH. Dimulai dari A.R. Radcliffe Brown yang mengatakan hukum adalah
suatu sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat
yang berada dalam suatu bangunan negara. Alasannya, hanya dalam suatu
organisasi sosial seperti negara terdapat pranata-pranata hukum seperti polisi,
pengadilan, penjara dan lain-lain sebagai pranata neara yang mutlak harus ada
untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam
masyarakat-masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai
suatu negara tidak mempunyai hukum. Walaupun tidak mempunyai hukum, ketertiban
sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang
ditaati oleh warga masyarakat secara otomatis-spontan (automatic spontaneus submission to tradition).
Pendapat Brown ini, yang mengatakan bahwa
hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu
negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial terdapat dalam setiap
bentuk masyarakat. Hukum dalam masyarakat sederhana, dikritik oleh Bronislaw
Malinowski dalam bukunya Crime and
Punishment in Savage Society yang terbit tahun 1926menurut Malinowski juga
bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis, tetapi
hukum harus diberi pengertian luas, yaitu sebagai suatu sistem pengendalian
sosial (legal order system) yang
didasarkan pada prinsip timbal-balik (principle
of reciprocity) dan publisitas (principle
of publicity) yang secara empiris
berlangsung dalam kehidupan masyarakat.
Pendapat Malinowski ini memperoleh komentar dan kritik dari Paul
Bohannan (Law and Warfare, Studies in the
Anthopology of Conflict, 1967:45-49) yang mengatakan sebagai berikut:
1.
Mekanisme resiprositas dan
publisitas sebagai kriteria untukmengatur hak dan kewajiban dalamkehidupan
masyarakat pada dasarnya bukanlah merupakan hukum, tetapi hanya merupakan suatu
kebiasaan (custom) yang digunakan
masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial.
2.
Pengertian hukum harus dibedakan dengan tradisi (tradition) atau kebiasaan, atau lebih spesifik norma hukum
mempunyai pengertian yang berbeda dengan kebiasaan. Norma hukum adalah peraturan
yang mencerminkan tingkah laku yang seharusnya (ought) dilakukan dalam hubungan antar individu. Sedangkan
kebiasaan merupakan seperangkat norma
yang diwujudkan dalam tingkah laku dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama.
Kadang kala kebiasaan bisa sama dan sesuai dengan hukum, tetapi bisa juga
bertentangan dengan norma-norma hukum.
Oleh karena itu Bohannan mengajukan definisi
hukum sebagai seperangkat kewajiban yang dipandang sebagai hak warga masyarakat dan kewajiban
bagi warga masyarakat yang lain, yang telah dilembagakan ulang menjadi
institusi hukum untuk mencapai tujuan agar kehidupan masyarakat dapat berfungsi
dan teratur. Karena itu, dikatakan bahwa resiprositas berada pada basis
kebiasaan, tetapi kebiasaan yang telah dilembagakan sebagai norma hukum melalui
tahapan yang disebut double
institutionalization of norm atau pelembagaan kembali norma.
Selanjutnya, Leopold Pospisil (Anthopology of Law, A Comparative Study,
1971: 39-35) juga mengkritik Malinowski bahwa pengertian hukumnya terlalu luas,
sehingga hukum yang dimaksudkan juga dimaksudkan juga mencakup pengertian
kebiasaan-kebiasaan, bahkan semua bentuk kewajiban-kewajiban yang berhubungan
dengan aspek religi dan juga kewajiban-kewajiban yang bersifat moral dalam
kehidupan masyarakat. Untuk itu Pospisil mengajukan definisi hukum sebagai
suatu aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai alat untuk pengendalian
sosial. Untuk membedakan peraturan hukum dengan noram-norma lain, yang
sama-sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial, maka peraturan
hukum dicirikan mempunyai 4 atribut (attributes
of law) yaitu :
1.
Atribut kekuasaan/otoritas (attribute
of authority), adalah keputusan-keputusan
dari pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa.
2.
Atribut penerapan secara universal (attribute
of intention of universal aplication)
artinya keputusan-keputusan pemegang
otoritas juga akan diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa yang sama secara
universal.
3.
Atribut obligasio (attribute of
obligation) berarti keputusan
pemegang otoritas tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa pihak pertama
memiliki hak untuk menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai
kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama.
4.
Atribut sanksi (attribute of
sanction) keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas tersebut juga
disertai penjatuhan sanksi.
Dalam konteks hukum adat di Indonesia, konsep
hukum yang semata-mata berdasarkan atribut otoritas, juga diperkenalkan oleh
Ter Haar dengan teorinya teori Keputusan
(beslissingenleer/ decision theory) yang
mendefinisikan hukum sebagai keputusan-keputusan kepala adat terhadap kasus
sengketa dan non sengketa
Fase Pluralisme Hukum (1940-sekarang)
Fase ini terbagi menjadi sub-sub fase antara
lain: 1) Fase antropologi hukum penyelesaian sengketa (1940-1950-an); 2). Fase
pluralisme hukum penyelesaian sengketa dan non sengketa (1960- 1970-an); 3).
Fase pluralisme hukum pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan
lain-lain (1990- sekarang).
Pada fase AH penyelesaian sengketa,
teori-teori evolusionisme dan fungsionalisme mulai ditinggalkan dan
bergeser ke arah untuk memahami mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa (dispute settlement) dalam masyarakat.
Metode penelitian juga sudah berganti dari studi pustaka/dokumen menjadi studi
lapangan (fields research). Karya klasik dari Karl Llewellyn dan E.A. Hoebel bertajuk The Cheyenne Way (1941) merupakan hasil
studi lapangan kolaborasi dari seorang sarjana hukum (Llewellyn) dengan ahli
antropologi (Hoebel) dalam masyarakat
Indian Cheyenne di AS. Kemudian Hoebel mempublikasikan hasil studinya dengan
judul The Law of Primitive Man (1954),
disusul karya Gluckman mengenai hukum orang Barotse dan
lozi di Afrika, juga karya Bohannan
mengenai hukum orang Tiv, dan Gulliver mengenai hukum orang Arusha dan Ndenduli, serta karya Pospisil tentang hukum
orang Kapauku di Papua. Pada
fase ini, kajian yang menonjol adalah penemuan hukum dengan menelusuri kasus
sengketa. Pada masa itu, untuk menemukan hukum pada masyarakat yang belum
mengenal tulisan dipakai metode 3 jalan raya hukum yaitu :
1.
Metode ideologis, adalah cara
penemuan hukum dengan mencari aturan atau norma yang dipersepsikan sebagai
hukum/pedoman perilaku.
2.
Metode deskriftif, ialah cara
penemuan hukum dengan mengamati perilaku anggota masyarakat untuk
diabstraksikan menjadi hukum.
3.
Metode kasus sengketa, adalah
cara penemuan hukum dengan mengikuti, mengamati dan menelaah kasus yang telah
atau sedang terjadi di masyarakat.
Menurut Hoebel, metode pertama dan kedua
mempunyai kelemahan yaitu pada metode pertama kita hanya mendapatkan aturan
yang belum tentu dipraktekkan dalam kasus yang sedang dihadapi. Sedangkan pada
metode kedua, perilaku yang muncul belum tentu menunjukkan keadaan yang
sebenarnya, jika sedang menghadapi sengketa. Oleh karena itu, metode ketiga
sangat cocok dan komplit, karena di dalamnya kita dapat menemukan apa yang
ditemukan dalam metode pertama dan kedua. Selain itu metode ini dipandang lebih
ilmiah karena menerapkan metode induktif (dari khusus ke umum).
Dalam kepustakaan sosiologi sengketa disebut
dengan konflik. Pengertian konflik adalah fenomena sosial yang bersifat semesta
(universal) dan melekat (inherent) dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu
konflik tidak perlu dilihat sebagai gejala patologis yang bersumber dari
tingkah-laku devian/abnormal, karena setiap komunitas masyarakat mempunyai kapasitas untuk
menciptakan norma-norma dan mekanisme-mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan
konflik-konflik yang muncul dalam pergaulan sosial warga masyarakat.
Dalam perspektif antropologi hukum, fenomena
konflik mempunyai makna ganda yaitu makna negatif dan makna positif. Makna
negatif, konflik menimbulkan disintegrasi suatu kehidupan sosial dan melemahkan
kohesi sosial atau menimbulkan kerusakan suatu sistem hubungan sosial dalam masyarakat. Makna
positif, konflik dapat mempertahankan integrasi sosial, memperkokoh ikatan
sosial, memberi kontribusi untuk mengembalikan keseimbangan hubungan sosial
antar individu atau kelompok. Makna positif akan terwujud jika pihak-pihak yang
terlibat konflik secara bersama-sama dapat mengelola, mengendalikan, dan
menyelesaikan konflik yang dihadapi secara dewasa, bijak, damai, dengan atau
tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga (Gluckman, 1956).
Secara umum dikatakan bahwa terjadinya konflik
dalam masyarakat bersumber dari persoalan-persoalan sebagai berikut:
1.
Penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam (natural resources control and distribution)
2.
Ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelomok masyarakat (terittoriality
expantion)
3.
Kegiatan ekonomi masyarakat (economic
activities); dan
4.
Kepadatan penduduk (density of
population).
Dalam persepktif AH, konflik yang terjadi
dalam masyarakat paling tidak dapat dikategorisasi menjadi 3 macam, yaitu :
1.
Konflik kepentingan (conflict of interests)
2.
Konflik nilai-nilai (conflict of
values)
3.
Konflik norma (conflict of norms).
Nader dan Todd (1978) menyatakan bahwa pada
dasarnya konflik-konflik yang terjadi di
masyarakat melalui tahapan-tahapan konflik sebagai berikut :
1.
Pra konflik, adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang,
bersifat monadik
2.
Konflik, adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui
adanya perasaan tidak puas tersebut, bersifat diadik.
3.
Sengketa, adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum
atau melibatkan pihak ketiga, bersifat triadik atau publik.
Sedangkan model-model penyelesaian konflik
yang dikenal dalam masyarakat sederhana maupun modern adalah sebagai berikut :
1.
Membiarkan saja (lumping it),
salah satu pihak tidak menanggapi keluhan, gugatan, tuntutan pihak lain atau
mengabaikan konflik yang terjadi dengan pihak lain
2.
Menghindar (avoidance), salah
satu pihak menghindari konflik karena tidak berdaya atau untuk menjaga hubungan
dengan pihak lain.
3.
Kekerasan (coersion),
penyelesaian dengan mengandalkan kekuatan fisik dan kekerasan, seperti
melakukan tindakan hukum sendiri (self-helf
atau eigenrichting) atau bentuk perang antar suku (warfare)
4.
Negosiasi, melalui proses kompromi antara pihak-pihak yang berkonflik
5.
Mediasi, melalui kesepakatan antara pihak-pihak untuk melibatkan pihak
ketiga (mediator dalam penyelesaian konflik, walau hanya berfungsi sebatas
perantara (go-between) yang bersifat
pasif, karena inisiatif untuk mengambil keputusan tetap didasarkan pada
kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik
6.
Arbitrase, melalui kesepakatan untuk melibatkan pihak ketiga yang
disebut arbitrator sebagai wasit yang memberi keputusan dan keputusan tersebut
harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkonflik
7.
Ajudikasi, melalui institusi pengadilan yang keputusannya mengikat para
pihak.
Sistem nilai, norma, politik, ekonomi, dan
keyakinan sangat mempengaruhi pilihan bentuk institusi dan model-model
penyelesaian konflik dalam masyarakat. Institusi penyelesaian konflik yang
dikenal dalam masyarakat paling tidak ada 2 macam , yaitu:
1.
Institusi tradisional (folk
institutions), biasanya dipilih oleh masyarakat yang masih sederhana dan
subsisten, di mana relasi antar individu, hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka
maksud penyelesaian sengketa adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis
dalam masyarakat.
2.
Institusi negara (state
institutions), biasanya dipilih oleh masyarakat yang sudah kompleks dan
modern, di mana relasi sosial lebih bersifat individualistik, berorientasi pada
ekonomi pasar, maka maksud penyelesaian sengketa dengan mengacu pada hukum
negara yang legalistik.
Daniel S.Lev, Indonesianis dari Amerika
Serikat (1972) pernah melakukan penelitian
mengenai budaya hukum penyelesaian sengketa masyarakat pedesaan di Jawa
dan Bali menyimpulkan sebagai berikut :
1.
Dalam kehidupan sosial sebagai besar masyarakat Indonesia cenderung
untuk menghindari konflik dengan siapapun, karena nilai-nilai pergaulan sosial yang dianut
lebih bersifat personal, komunal, mengutamakan solidaritas, dan bernuansa
magis. Oleh karena itu jika terjadi konflik, cenderung diselesaikan melalui prosedur kompromi, konsiliasi,
mengutamakan pendekatan personal dan kekerabatan.
2.
Konflik antar individu sedapat mungkin dihindari, dan kalaupun harus terjadi cenderung ditutupi dengan gaya
yang halus, tidak merusak hubungan/pergaulan sosial, tidak menjatuhkan
martabat/derajat pihak yang diajak konflik
3.
Fokus penyelesaian konflik bukan pada penerapan peraturan hukum, tetapi
lebih pada upaya pelenyapan konflik yang menjadi sumber ketegangan sosial.
4.
Makna penyelesaian konflik bukan pada persoalan kalah-menang (win-lose solution), tetapi menjadi
kewajiban para pihak untuk menghentikan perselisihan dan meniadakan ketegangan
sosial yang telah terjadi. Oleh karen itu yang diutamakan bukan penyelesaian
substansi konflik tetapi lebih pada prosedur penyelesaian konflik.
5.
Para pihak yang berkonflik lebih melihat pihak ketiga (petugas hukum)
dari pada peraturan-peraturan hukum yang mengatur penyelesaian sengketanya.
Oleh karena itu petugas hukum ditaati masyarakat bukan karena alasan yang
berkaitan dengan masalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
Pada Fase Pluralisme Hukum
Penyelesaian Sengketa dan Non Sengketa, tema
kajian pluralisme hukum pada awalnya difokuskan pada fenomena kemajemukan cara
penyelesaian sengketa dalam masyarakat melalui mekanisme dan institusi
tradisional yang dikenali masyarakat setempat (folk institution of dispute settlement). Kemudian tema-tema studi
pluralisme model penyelesaian sengketa mulai diarahkan untuk memahami mekanisme dan institusi
penyelesaian sengketa selain menurut hukum yang diberlakukan pemerintah
kolonial di negeri jajahannya, juga menurut hukum positif yang berlaku di
negara-negara merdeka
Kemudian sejak tahun 1970-an tema studi AH
secara sistematis difokuskan pada korelasi antar institusi-institusi
penyelesaian sengketa secara tradisional dalam masyarakat menurut hukum rakyat
(folk law) dan menurut institusi
penyelesaian sengketa menurut hukum negara (state
law). Karya-karya Nader dan Todd, van Rouveroy van Nieuwaal, serta
suami-istri Franz dan Keebet von Benda Beckmann mewakili masa itu. Nader dan
Todd (1978) sebagai hasil riset dari Berkeley Village Law Project,
memfokuskan kajiannya pada proses-proses, mekanisme-mekanisme, institusi-institusi
penyelesaian sengketa yang dikenali dalam komunitas-komunitas masyarakat
tradisional maupun masyarakat modern di sepuluh negara di dunia. Kemudian
Nieuwaal melakukan riset tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam
kehidupan orang Togo di Afrika. Selanjutnya Franz von Benda Beckmann (1979) dan
Keebet von Benda Beckmann (1984) memberi pemahaman tentang proses,mekanisme dan
institusi penyelesaian sengketa mengenai harta warisan di kalangan orang
Minangkabau menurut pengadilan adat dan pengadilan negeri di Sumatera Barat.
Karya Sally Falk Moore (1978) mulai meninggalkan tema pluralisme hukum
penyelesaian sengketa berganti tema pluralisme hukum di luar penyelesaian
sengketa, dengan penelitiannya tentang persoalan agraria pada suku Chagga di
Tanzania (Afrika), mekanisme dalam proses produksi di satu pabrik garment
terkenal di Amerika Serikat. Selain itu pada tahun 1970-an kajian AH
menggunakan pendekatan sejarah untuk menjelaskan keberadaan, relasi dan
interaksi institusi hukum negara dengan hukum rakyat dalam penyelesaian
sengketa, seperti yang dilakukan Keebet
von Benda Beckmann dalam karyanya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat: Peradilan Nagari dan Pengadilan
Negeri di Minangkabau (2000).
Berikutnya kajian pluralisme hukum dalam
berbagai hal mengemuka sejak 1970-an. Pluralisme hukum menurut Griffiths
(1986:1) didefinisikan sebagai situasi dimana dua atau lebih sistem hukum
bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama.
Sedangkan Hooker (1975:3) menjelaskan pluralisme hukum sebagai situasi dimana
dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial. Sementara
itu Franz von Benda Beckmann mengartikan pluralisme hukum sebagai suatu kondisi
dimana lebih dari satu sistem hukum atau
institusi bekerja secara berdampingan
dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat.
Ajaran mengenai pluralisme hukum (legal pluralism) secara umum
dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (legal centralism). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai
suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara sebagai satu-satunya
hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan eksistensi sistem-sistem
hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan, dan semua bentuk
mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara empiris berlangsung dalam
kehidupan masyarakat. Jadi ideologi sentralisme hukum cenderung mengabaikan
kemajemukan sosial dan budaya dalam masyarakat.
Oleh karena itu pemberlakuan sentralisme hukum dalam suatu komunitas masyarakat
yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya hanya merupakan sebuah
kemustahilan.
Menurut Griffiths, pluralisme hukum pada
dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pluralisme hukum yang kuat dan
pluralisme hukum yang lemah. Pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism)
mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok
masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak ada hirarki yang
menunjukkan hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain.
Sedangkan pluralisme hukum yang lemah, merupakan bentuk lain daripada
sentralisme hukum, karena walaupun hukum negara mengakui adanya sistem-sistem
hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior,
sementara sistem hukum yang lain
bersifat inferior. Contoh konsep pluralisme hukum yang lemah, adalah interaksi
sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat dan hukum agama
yang berlangsung di negara-negara jajahan.
Setelah munculnya teori Semi Autonomous
Social Field dari Sally Falk Moore (1978), maka Griifths mengadopsi teori Moore, sehingga hukum yang dimaksud
dalam konsep pluralisme menjadi tidakt terbatas pada sistem hukum negara, hukum
kebiasaan, atau hukum agama saja, tetapi kemudian diperluas termasuk juga
sistem normatif yang berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self-regulation). Pada tahap
perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan
ko-eksitensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses,
dan institusi hukum dalam masyarakat.
Pada
tahun 1970-an tema studi-studi AH cenderung lebih diarahkan untuk memberi
pemahaman mengenai fungsi dan peran hukum dalam fenomena pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, seperti ditunjukkan karya bersama Joop Spiertz
dan Melanie G.Wiber (eds) yang bertajuk The
Role of Law in Natural Resources Management (1996). Kecenderungan lainnya,
pada April 2002 The Commission on Folk Law and Legal Pluralism menyelenggarakan
the XIII-th International Congress and Symposium di Chiang Mai, Thailand dengan
tajuk Legal Pluralism and Unofficial Law
in Social, Economic and Political Development. Selanjutnya perkembangan terakhir pada bulan
Juni 2006 lalu di Universitas Indonesia, Jakarta The Commisionon Folk Law dan
Legal Pluralism kembali menyelenggarakan Kongres dan Simposium Internasional
dengan tema Law, Power and Culture:
Transnational, National and Local Process in the Contex of Legal Pluralism. Pada
Kongres ini selain berfokus pada kemajemukan pengelolaan dan hak penguasaan
masyarakat adat atas sumber daya alam, juga dibahas topik kajian hukum
ber-perspektif jender, agama dan kemajemukan hukum, regulasi hak asasi manusia,
perlindungan HKI, masalah jaminan sosial, KDRT, trafficking (perdagangan manusia), hak atas kesehatan reproduksi,
sampai aspek penanggulangan bencana alam.
IV. TEORI-TEORI ANTROPOLOGI HUKUM
Teori Forum Shopping-Shopping Forum dari
Keebet von Benda Beckmann (2000: 64-65) merupakan hasil penelitiannya di
Sumatera Barat yang berlangsung bulan Juni 1974 – September 1975. Teori ini
dibangun dari fakta persengketaan harta warisan kolam Batu Panjang yang diklaim
oleh dua kaum yang berbeda. Dari fakta-fakta penelitian itu, Keebet membangun
sebuah teori yang di-analogkan dari istilah hukum perdata internasional,
yaitu Forum Shopping-Shopping Forum. Forum
Shopping berarti orang-orang yang bersengketa dapat memilih lembaga dan mendasarkan
pilihannya pada hasil akhir apakah yang diharapkan dari sengketa tersebut.
Sedangkan Shopping Forum berarti
pihak pengadilan, baik pengadilan adat ditingkat masyarakat maupun di
pengadilan pemerintah terlibat memanipulasi sengketa yang diharapkan dapat
memberikan keuntungan politik atau malah menolak sengketa yang mereka (hakim)
kawatirkan akan mengancam kepentingan mereka.
Dikaitkan dengan kondisi sekarang ini, pada Forum Shopping, para pihak yang
bersengketa bebas memilih model penyelesaian sengketa apakah melalui jalur di
luar pengadilan (ADR) ataukah di pengadilan sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan.
Sedangkan Shopping Forum, pihak
lembaga penegak hukum (polisi, jaksa,hakim, juga advokat) mempunyai kekuasaan
apakah akan meneruskan perkara yang diajukan kepadanya ataukah
dipeti-eskan/deponeer/SKPP/ SP3 sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan.
Teori berikutnya dari Marc Galanter (dalam
Ihromi,1993) yang bertajuk Justice in
Many Rooms. Pada masa itu terjadi dua pandangan yang berbeda tentang hukum,
di satu sisi dilihat dalam kacamata sentralisme hukum, sedangkan yang lain
melihatnya dari dimensi pluralisme hukum. Galanter melihat bahwa pada dimensi
sentralisme terdapat kelemahan-kelemahan, seolah-olah keadilan itu produk
eksklusif dari lembaga yang mendapat wewenang yuridis dari negara. Dengan
demikian ada gerak sentripetal dari masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya,
artinya satu-satunya cara untuk mencari keadilan hanya ditemukan di temukan di
lembaga peradilan yang dibentuk oleh pemerintah. Akibatnya terjadi banyak
penumpukan perkara (terutama di MA) sehingga membutuhkan waktu yang panjang,
tenaga dan biaya yang berlebih.
Di Amerika Serikat, dengan menunjuk studi
S.Macaulay, bahwa banyak sengketa yang menurut peraturan atau perjanjian bisa
diajukan ke pengadilan, ternyata banyak
yang dibiarkan berlalu, dielakkan, dibatalkan, atau diselesaikan sendiri
melalui jalur ADR (Alternative Dispute
Resolution). Melihat kenyataan yang demikian, Marc Galanter berpendapat
bahwa setiap komunitas biasanya mempunyai self
regulation termasuk dalam penyelesaian
sengketa yang tejadi diantara
mereka. Hingga akhirnya, Marc Galanter mencetuskan teori Justice in Many Rooms yang mengatakan bahwa keadilan itu dapat
ditemukan diberbagai tempat, tidak hanya di lembaga peradilan yang dibentuk
oleh pemerintah.
Aplikasi teori Galanter di Indonesia yang
bernuansa pluralistik dapat kita temukan, misalnya negosiasi, mediasi,
arbitrase baik sengketa tentang rumah tangga, di tempat kerja, perdagangan dan
lain sebagainya. Contoh konkritnya lembaga bipartit dan tripartit untuk
sengketa perburuhan, mediasi kasus pencemaran sungai Tapak di Semarang dan
sungai Asahan di Sumatera Utara untuk sengketa lingkungan, peran orang
tua/sesepuh untuk perkara rumah tangga dan masih banyak lagi. Bahkan sejak
tahun 1999 pemerintah telah memberikan wadah dengan dikeluarkannya Undang Undang
No.30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.
Selanjutnya teori Semi Autonomous Social Fields (dalam Ihromi, 1993) yang
merupakan hasil penelitiannya di bidang
agraria di Tanzania, tepatnya pada suku Chagga. Latar belakang munculnya teori
ini bermula dari adanya dikotomi tentang hukum, dari Roscoe Pound dan Cochrane.
Ahli sosiologi hukum Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum itu berfungsi sebagai
alat untuk merubah/merekayasa masyarakat (law
as a tool of social engeneering), artinya dengan pemberlakuan hukum dari
pemerintah maka perilaku masyarakat
dapat diarahkan sesuai dengan hukum tersebut (perubahan sosial). Sebaliknya
Cochrane mengemukakan bahwa masyarakatlah yag menentukan hukum, bukan
masyarakat yang diarahkan oleh hukum dari pemerintah.
Dengan bekal pendapat yang kontradiktif
tersebut, Moore ingin membuktikannya dengan melakukan penelitian pada Suku
Chagga di Tanzania yang sedang diberlakukan UU Agraria yang baru yang intinya
tidak ada lagi tanah milik pribadi tetapi semua tanah milik negara, setiap
warganegara hanya mempunyai hak menggarap. Ternyata penerapan UU tersebut oleh
pemerintah Tanzania yang sosialis, tidak mencapai hasil yang diharapkan.
Orang-orang yang dulunya tuan tanah, dan sekarang tanahnya diambil oleh negara
dan kemudian diberi tanah garapan yang luasnya sama dengan lainnya, ternyata
secara terselubung tetap menjadi “tuan tanah”, karena jika ada orang yang
dulunya tidak punya tanah kemudian dengan UU baru dia dapat tanah, tidak dapat
menggarap tanah tersebut karena tidak punya biaya. Kemudian yang terjadi,
secara diam-diam tanahnya dijual sedikit kepada “tuan tanah” untuk memperoleh
uang. Sehingga yang terjadi keadaan kembali seperti sebelum adanya UU Agraria,
yang tuan tanah kembali jadi tuan tanah, yang miskin tetap miskin.
Akhirnya muncul satu teori dari Semi Autonomous Social Fileds dari Sally
Falk Moore yang mengatakan bahwa dalam suatu bidang kehidupan sosial secara
internal dapat membangkitkan aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, sistem-sistem,
tetapi di lain pihak juga rentan menjadi sasaran dari aturan-aturan dan
kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari eksternal yang mengitarinya.
Teori terakhir dari Michel Lipsky yang
bertajuk Street Level Bureaucracy (dalam
Masinambouw, 2000:168) berpendapat bahwa para birokrat tingkat bawah yang
langsung berhadapan dengan masyarakat mengamban dua tugas sekaligus: 1).
sebagai pelaksana peraturan/kebijakan; 2). dalam diri mereka melekat diskresi
(kebijaksanaan). Teori Steet Level
Bureaucracy mengatakan bahwa ada
kecenderungan birokrat tingkat bawah untuk melakukan diskresi yang
menguntungkan dirinya sendiri. Berbagai contoh di Indonesia, adalah
pungutan-pungutan liar untuk mengurus KTP, SIM, Paspor, perijinan, sertifikat
tanah, bahkan termasuk pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.
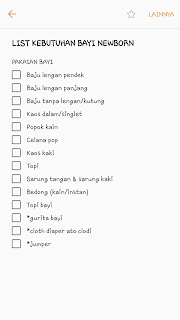
Komentar
Posting Komentar